 |
| Ilustrasi |
“Ubi Societas Ibi Ius, di mana
ada masyarakat, di situ ada hukum.” Demikian adagium yang pernah diungkapkan
Marcus Tullius Cicero, seorang ahli hukum Romawi yang hidup antara 106-43
SM. Ungkapan ini bermakna bahwa hukum lahir dan terbentuk akibat dari pola
interaksi sesama anggota masyarakat yang mengandung nilai-nilai dan hubungannya
terhadap alam dimana ia tinggal serta melangsungkan kehidupan secara
turun-temurun hingga pada akhirnya membentuk kebudayaan.
Dalam konteks masyarakat adat,
hukum yang terbentuk adalah hukum adat, yang mendasarkan sistem kehidupannya
pada adat-istiadat yang mencakup larangan dan kebiasaan yang telah diwariskan
secara turun-temurun dan berkelanjutan. Pentingnya pengakuan terhadap
masyarakat adat dalam bentuk undang-undang bukan saja dapat memberikan jaminan
kepastian hukum kepada masyarakat adat, tetapi lebih jauh dari itu, yakni
menjamin tercapainya keadilan bagi masyarakat adat.
Legal Standing
Jika ditarik ke belakang,
eksistensi Hukum Adat telah menjadi pembahasan dalam pembentukan UUD 1945 saat
sidang BPUPKI dan PPKI oleh Soepomo dan Muhammad Yamin, yang mengemukakan
pendapat agar hukum adat mendapat pengakuan di dalam konstitusi yang akan dibentuk.
Soepomo menyampaikan bahwa hak asal usul dalam daerah-daerah yang
bersifat istimewa harus diperingati juga. (Bahar, 2008). Demikian juga
dengan Muhammad Yamin menyampaikan bahwa kesanggupan dan kecakapan bangsa
Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul
beribu-ribu tahun yang lalu (Taqwaddin, 2010).
Setidaknya, terdapat 27 ketentuan
yang telah mengatur eksistensi masyarakat adat di Indonesia selain Pasal 18B
ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni: Pasal 4 Tap
MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria,
Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai
Keanekaragaman Hayati, Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Pasal 6 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 9 ayat (2)
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 67 ayat (1) UU. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1
angka 33 UU No. 1 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 43 UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Minerba, Pasal 1 angka 31 dan Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2004
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Pasal 40 UU
No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum, Pasal 1 huruf p dan Pasal 1 huruf r UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 142 dan Pasal 149 ayat (1) UU No. 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 1 angka 1, Pasal 96, dan Pasal 97 UU
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pengakuan Internasional
Secara global, masyarakat adat
atau biasa disebut indigenous peoples telah mendapat pengakuan. Hal ini
terlihat dari beberapa kesepakatan internasional atas eksistensi masyarakat
adat, yakni Convention of International Labor Organisation Concerning
Indigeneous and Tribal People in Independent Countries (1989), Deklarasi
CariOca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janairo
(1992), Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chiang Mai
(1993), De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan oleh United
Nations World Conference on Human Rights (1993). Saat ini istilah indigenous
people semakin resmi digunakan sejak lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People)
pada tahun 2007.
Dinamika Legislasi
Sejak tahun 2007, usulan untuk
membentuk undang-undang yang khusus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak
konstitusional bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia pernah masuk dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas). Begitu juga tahun 2014 dan 2017. Namun nasib
Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat belum mendapat kepastian
hukum.
Di tahun 2018 yang lalu, RUU ini
kembali masuk dalam Prolegnas prioritas DPR. Pada tanggal 9 Maret
2018, Presiden Joko Widodo pernah mengeluarkan Surat Perintah Presiden
(Surpres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No B-186 yang mengatur tentang
pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR
(Mongabay, 13/12/2019). Dan pada 14 Januari 2021 yang lalu, dikeketahui bahwa
RUU ini tetap masuk dalam Prolegnas prioritas yang ditetapkan oleh
Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat kerja bersama Menkumham dan DPD RI
(Jawapos, 23/3).
Problem Pendataan
Menurut laporan UN Permanen
Forum on Indigenous Issue (2014) memperkirakan jumlah indigenous peoples
sekitar 370 juta jiwa. Dan 2/3 dari jumlah tersebut tinggal di Asia. (Arizona,
2014). Pada tahun 2000, Departemen Sosial mencatat kelompok Komunitas Adat
Terpencil (KAT) sebanyak 242.514 kepala keluarga (KK) atau 1.212.575 jiwa
yang tersebar di 18 provinsi. Populasi kebanyakan terdapat di Papua,
Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Pada tahun 2006, Departemen Sosial
melakukan pemetaan kembali yang kemudian dimutakhirkan pada tahun 2008 dan
menghasilkan jumlah populasi KAT sebanyak 229.479 KK. Kementerian Negara
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menyebutkan jumlah penduduk yang
tinggal di desa hutan mencapai 33.512.845 jiwa. Sementara menurut Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), jumlah masyarakat adat di Indonesia sebanyak
80 juta jiwa (Cahyaningrum, 2015).
Pengakuan Hutan Adat
Hingga tahun 2019, pemerintah
melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan luas hutan
adat sebanyak 34.569 Hektare dari 574.119 luas wilayah indikatif hutan adat
(Antaranews, 9/8/2019). Luas hutan adat ini bertambah dari 17.243 Hektar di
tahun 2018. Namun luas wilayah indikatif hutan adat versi Kementerian LHK ini
masih jauh dari usulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yakni 9,6 juta
hektare.
Menurut AMAN, Indonesia
membutuhkan waktu hampir 200 tahun untuk mengakui jumlah minimum hutan adat di
Indonesia jika menggunakan percepatan pengakuan hutan adat versi Kementerian
LHK (RMI, 2019).
Pengakuan negara terhadap
keberadaan Masyarakat Hukum Adat merupakan bentuk kewajiban negara di dalam
pemenuhan hak asasi warga secara legal formal yang di dalamnya mencakup
perlindungan Masyarakat Hukum Adat dari ancaman ekspansi modal lewat korporasi
perkebunan dan kehutanan. Perlindungan yang dimaksud disini mencakup aspek
wilayah adat, pranata adat, lembaga adat, dan tradisi adat. Dengan demikian,
dibutuhkan undang-undang sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Masyarakat Hukum Adat.
Di sisi lain, konflik tenurial
antara Masyarakat Hukum Adat dengan korporasi swasta, kepentingan perusahaan
yang dikelola oleh pemerintah, maupun perseorangan telah terjadi sejak
Indonesia belum ada hingga kini. Pertanyaannya, bilakah negara, melalui
Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, bersedia mengeluarkan areal-areal milik
masyarakat adat yang sebelumnya pernah diklaim lewat hak istimewa (perizinan)
yang diterbitkan bagi korporasi swasta maupun perusahaan yang dikelola
pemerintah, seperti izin Hak Guna Usaha (HGU)?
Selain itu, proses pengakuan
terhadap masyarakat hukum adat tidak diatur secara memadai, tumpang tindih, dan
sektoral. Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, prosedur pengukuhan
keberadaan masyarakat adat melalui Perda. Sementara, dalam Permendagri No. 52 Tahun
2014 tentang Tatacara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur
penetapan Masyarakat Hukum Adat melalui Keputusan Kepala Daerah, yakni
Bupati/Walikota atau Gubernur. Hal yang sama juga terdapat dalam Permen ATR No.
10 Tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat
Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu ditetapkan melalui
Keputusan Kepada Daerah.
Terkait dengan proses dalam
memperoleh pengakuan ini, masyarakat adat akan berbenturan dengan mental
pejabat dan birokrasi mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Lagi-lagi hal ini
kembali kepada komitmen politik (political will) Kepala Daerah beserta
legislatif daerah dalam membuat prioritas kebijakan yang berpihak kepada
Masyarakat Hukum Adat di wilayah kekuasaannya, mulai dari pendataan hingga
penerbitan keputusan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat.
Kepala daerah harus mampu
menggerakkan mesin birokrasi di wilayah yang termasuk dalam Wilayah Adat untuk
mempercepat proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat agar efektif, efisien, tidak
bertele-tele, serta tidak diskriminatif. Istilah “jemput bola” mungkin lebih
tepat digunakan dalam upaya melakukan inventarisasi komunitas-komunitas
Masyarakat Hukum Adat, pemetaan Wilayah Adat, hingga penetapan tapal batas yang
merupakan wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat.
Kiranya pengakuan negara terhadap
Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk undang-undang nantinya tidak menjadi beban
bagi masyarakat adat dalam memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.
Dan semoga RUU Masyarakat Hukum Adat mendapat pengesahan yang tidak terlalu
lama dan menjadi solusi atas problem yang selama ini dihadapi masyarakat
adat.***
(Dimuat di Koran ANALISA,
edisi Jumat 30 April 2021)


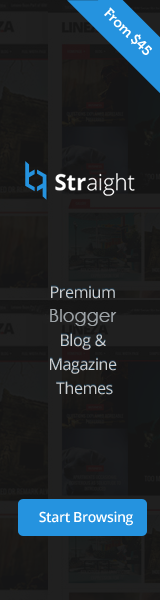











Tidak ada komentar
Posting Komentar